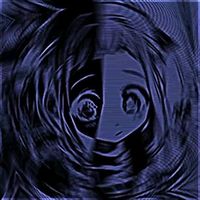Enam mahasiswa—Raka, Nando, Dimas, Citra, Lala, dan Novi—memutuskan untuk menghabiskan libur semester dengan mendaki sebuah bukit yang jarang dikunjungi di pinggiran kota kecil. Mereka mencari petualangan, udara segar, dan momen kebersamaan sebelum kembali ke rutinitas kampus. Namun, yang mereka temukan bukanlah keindahan alam, melainkan kengerian yang tak terbayangkan.
Bukit itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Menurut penduduk setempat, kawasan itu dijaga oleh makhluk halus yang disebut “penunggu hutan”, sosok jin yang berwujud manusia tampan dan wanita cantik, yang gemar memperdaya manusia muda untuk dijadikan teman di alam mereka. Awalnya, keenamnya menertawakan cerita itu—hingga malam pertama di hutan tiba.
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Juan Darmawan, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
Siapakah Itu?
Di desa Mekar Sari, sore itu awalnya langit tampak cerah. Beberapa anak-anak warga masih sempat bermain di jalan.
Tapi perlahan, awan kelabu mulai menggantung di atas perbukitan. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang tak biasa.
Dedaunan pohon pisang di tepi jalan mulai bergetar, disusul bunyi genting bergemeretak di atap rumah warga.
Pak Arman yang masih di depan rumah Ki Waryo menatap langit dengan dahi berkerut.
“Sep, ini aneh… mendungnya datang dari arah gunung Arga Dipa,” katanya pelan.
Pak Asep ikut menatap ke atas, wajahnya ikut tegang.
“Iya, Man. Anginnya juga bukan angin biasa… rasanya berat, seperti bawa sesuatu.”
Petir menyambar di kejauhan, menyinari langit kelabu dan menggema ke seluruh desa. Warga mulai menutup jendela rumah, dan anjing-anjing hutan terdengar menggonggong ke arah gunung tanpa henti.
“Kita harus ke sana sebelum malam turun,” kata Pak Arman tegas.
“Kalau tidak, mungkin besok mereka tak akan bisa turun lagi.”
Ki Waryo menatap langit yang semakin gelap, wajahnya serius dan matanya tajam menembus kabut di kejauhan. Suara petir bergemuruh lagi, membuat udara di sekitar mereka terasa berat dan menekan.
“Kita ndak bisa naik ke gunung Arga Dipa sebelum malam Jumat Kliwon,” katanya pelan tapi tegas.
Pak Asep spontan menoleh.
“Lha, Ki… kenapa harus nunggu sampai malam Jumat Kliwon? Mereka itu masih di atas gunung, Ki. Kalau hujan makin deras, bisa bahaya!”
Ki Waryo menggeleng pelan, menggenggam tongkat kayunya lebih erat.
“Saya paham, Sep. Tapi kalian juga harus ngerti… gunung itu sedang ‘terjaga’. Saat seperti ini, batas dunia kita dan dunia mereka mulai menipis. Kalau kita maksa naik sebelum waktunya, kita bukan menolong— justru ikut terseret.”
Pak Arman menatap ke arah gunung yang kini puncaknya tertutup kabut pekat seperti asap hitam.
“Tapi Ki… kalau sampai besok malam, gimana nasib anak-anak itu?”
Ki Waryo menunduk sesaat, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Lalu ia berkata dengan suara pelan namun membuat bulu kuduk berdiri
“Kalau mereka masih bisa bertahan sampai malam Jumat Kliwon… artinya mereka memang diizinkan untuk turun. Tapi kalau tidak…”
Ia menghentikan ucapannya, menatap keduanya dengan pandangan tajam.
Ki Waryo tidak melanjutkan ucapannya justru meninggalkan Pak Arman dan Pak Asep yang masih berdiri di teras rumahnya.
Bu Sutini yang baru saja pulang dari warung berhenti di depan rumah Ki Waryo. Tangannya masih memegang payung yang sudah miring karena angin kencang. Ia melihat Pak Arman dan Pak Asep berdiri di teras dengan wajah cemas.
“Lho, ini kenapa toh, Pak? Kok pada tegang begitu?”
“Saya juga Ndak tahu Bu tiba-tiba angin kencang begini, mungkin karena gunung itu Bu,” ucap Pak Asep
Bu Sutini menatap ke arah gunung yang tertutup kabut.
“Astagfirullah… jadi beneran ya, gunung itu masih ada penunggunya. Bapak saya juga bilang begitu,”
Petir menyambar lagi di kejauhan, membuat mereka bertiga serempak menoleh ke arah puncak Arga Dipa yang kini tampak seperti bayangan hitam raksasa di balik langit kelabu semakin gelap,”
“Kalau begitu saya pamit dulu Pak Asep Pak Rahmat Assalamualaikum,”
Di puncak Gunung Arga Dipa, angin meraung seperti suara serigala lapar. Tenda milik para mahasiswa itu bergoyang hebat, sesekali nyaris terangkat dari tanah. Suara gesekan tali tenda dengan pasak menimbulkan bunyi creek… creek… yang membuat suasana semakin mencekam.
Novi memegangi bagian dalam tenda sambil berteriak,
“Raka! Pasaknya kayaknya mau copot! Anginnya kenceng banget!”
Raka yang duduk di dekat pintu tenda langsung merunduk keluar, berusaha menancapkan pasak lebih dalam. Wajahnya basah oleh air hujan yang menembus dari celah-celah tenda.
“Tahan aja dulu, Nov! Kalau roboh kita bisa kedinginan parah!”
Sementara itu para mahasiswa lain menggigil sambil memeluk lutut. Rencana untuk membuat api unggun gagal total kayu yang di kumpulkan basah kuyup.
Nando pun ikut keluar membantu Raka memperbaiki pasak tenda yang hampir copot.
“Dingin banget, Ndo… aku gak tahan,” katanya pelan, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan.
Nando tanpa sengaja mendengar suara aneh ia menoleh ke sampingnya — seperti suara langkah kaki berputar, diiringi bunyi gemerisik air hujan yang menimpa tanah. Dan di sanalah… ia melihat sesuatu.
Di tengah guyuran hujan deras dan kabut tebal, berdiri seorang wanita muda bergaun putih panjang. Gaunnya berkilau lembut diterpa kilat, rambut hitamnya terurai dan menempel di wajahnya. Wanita itu berputar pelan di antara genangan air, seperti sedang menari dengan irama yang hanya ia dengar sendiri. Gerakannya anggun—terlalu anggun untuk ukuran manusia biasa di tempat seterjal dan berlumpur seperti itu.
“Raka… lihat deh… ada yang…” suara Nando tercekat, ia tak bisa melanjutkan.
Raka mengerutkan alis, di tengah kedinginan karena basah kuyup dan angin berhembus kencang, Ia mendekat.
“Ada apa, Ndo?”
"Rak cewek itu cantik banget" Nando menunjuk ke arah wanita yang menari.
“Cewek? Cewek mana, Ndo?” tanya Raka heran, suaranya agak meninggi karena desiran angin yang kencang.
Nando menunjuk lagi, kali ini dengan jari yang sedikit gemetar.
“Itu, Rak! Di situ, deket batu besar! Dia lagi muter—pakai baju putih panjang!”
Raka menatap ke arah yang sama, matanya menyipit lebih dalam.
“Ndo, lu serius? Gak ada siapa-siapa di situ.”
Raka mengguncang bahu temannya.
“Woi! Nando! Jangan bengong gitu, lu kenapa sih?”
Nando hanya bisa berbisik pelan tanpa menoleh, suaranya serak,
“Rak… dia ngelihatin gue…”
“Ndo… lu ngapain?!” tanya Raka panik, tapi Nando seolah tak mendengar.
Raka yang masih jongkok di depan tenda, berusaha memperkuat pasak yang hampir tercabut angin, tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat Nando berjalan perlahan.
“Ndo! Mau ke mana lu?!” seru Raka sambil berdiri, tapi Nando tidak menjawab.
Tubuh Nando kaku, matanya kosong.
“Dung… deng… deng… dung…” suara gamelan terdengar jelas di telinga Nando membuat Nando perlahan menari mengikuti irama musik gamelan itu.
Raka menatap Nando dengan bingung.
Temannya itu berdiri di tengah hujan yang terus menerpa tubuhnya ia bergoyang perlahan, kedua tangannya melambai lembut seperti penari tradisional. Matanya setengah terpejam, wajahnya terlihat tenang tapi aneh—seolah sedang berada di dunia lain.
“Duh, Nando kenapa lagi, kok malah menari sendiri?” gumam Raka sambil mendekat.
Tapi yang membuat Raka makin heran, tidak ada suara apa pun selain hujan dan angin. Tidak ada gamelan, tidak ada irama. Hanya Nando yang tampak menari mengikuti sesuatu yang tidak terdengar.
“Ndo… lu denger apaan sih?” tanya Raka, kini sedikit cemas.
Nando tidak menjawab. Ia terus berputar, perlahan—kakinya melangkah menjauhi Raka tanpa alas kaki, melangkah ke lumpur yang mulai becek.
Raka panik, langsung menahan bahunya.