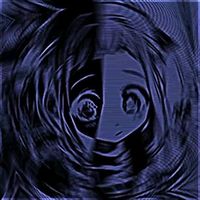Enam mahasiswa—Raka, Nando, Dimas, Citra, Lala, dan Novi—memutuskan untuk menghabiskan libur semester dengan mendaki sebuah bukit yang jarang dikunjungi di pinggiran kota kecil. Mereka mencari petualangan, udara segar, dan momen kebersamaan sebelum kembali ke rutinitas kampus. Namun, yang mereka temukan bukanlah keindahan alam, melainkan kengerian yang tak terbayangkan.
Bukit itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Menurut penduduk setempat, kawasan itu dijaga oleh makhluk halus yang disebut “penunggu hutan”, sosok jin yang berwujud manusia tampan dan wanita cantik, yang gemar memperdaya manusia muda untuk dijadikan teman di alam mereka. Awalnya, keenamnya menertawakan cerita itu—hingga malam pertama di hutan tiba.
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Juan Darmawan, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
Mimpi Buruk
Samidin dan Joko saling pandang sejenak, rasa penasaran mereka akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan cepat mereka mematikan pelita di teras rumah dan bergegas menyusul langkah Pak Arman, Pak Asep, dan Ki Waryo yang sudah mulai menjauh di jalan setapak.
“Pak! Tunggu dulu!” seru Joko sambil sedikit berlari kecil. Nafasnya tersengal ketika akhirnya mereka berhasil menyusul di tikungan jalan di dekat rumah Samidin dan Joko jalan yang menuju kaki bukit.
Pak Arman menoleh, sedikit terkejut.
“Lho, Samidin Joko? ada apa?”
Samidin mengusap keringat di dahinya.
“Pak Arman Pak kades Ki Waryo mau kemana malam-malam begini? Mau naik ke atas sana?,” tanya Samidin menunjuk bukit Arga Dipa dengan sorot matanya.
Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan di sekitar jalan bergoyang dan menimbulkan suara gesekan lirih.
“Iya, Din,” jawab Pak Arman dengan nada serius.
“Kami mau naik ke Arga Dipa malam ini.”
Joko mengerutkan dahi, menatap ke arah bukit yang gelap gulita.
“Tapi, Pak… malam-malam begini? Apa ndak bahaya?”
Pak Asep menatap keduanya dengan wajah tegang.
”Justru karena itu, Jo. Ada hal penting yang harus kami pastikan sendiri di atas sana.”
Samidin menelan ludah, masih terlihat ragu. “Ada hubungannya sama rombongan anak kuliah itu ya, Pak?”
Pak Arman menatapnya lama, tidak langsung menjawab. Sementara Ki Waryo yang dari tadi diam akhirnya bicara dengan suara berat dan dalam,
“Anak-anak itu bukan sedang mendaki biasa. Ada sesuatu yang mereka bawa tanpa sadar… sesuatu yang seharusnya tidak boleh di bawah.”
aku
Suasana mendadak sunyi. Hanya suara serangga malam yang terdengar bersahutan.
Joko melangkah setengah maju.
“Maksudnya gimana, Ki? Memangnya mereka bawa apa?”
Ki Waryo menatap bukit yang menjulang di hadapan mereka, matanya tajam tapi sendu.
“Nanti juga kalian lihat sendiri. Kalau memang mau ikut, silakan. Tapi sekali naik, jangan pernah menoleh ke belakang.”
Pak Asep menghela napas berat, lalu menyalakan senter.
“Ayo, waktunya berangkat. Sudah hampir tengah malam.”
Tanpa menunggu lagi, mereka bertiga — Pak Arman, Pak Asep, dan Ki Waryo — mulai melangkah menyusuri jalan setapak menuju kaki bukit Arga Dipa, sementara Samidin dan Joko saling berpandangan, ragu antara mengikuti atau kembali.
Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut.
“Sudahlah, Jo,” bisik Samidin.
“Sekali-sekali kita lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu.”
Joko mengangguk pelan, dan keduanya pun menyusul langkah rombongan,
Rombongan Pak Arman kini berjalan menembus rimbunnya pepohonan bambu. Di bawah sinar bulan yang temaram, batang-batang bambu menjulang tinggi, saling bergesekan diterpa angin malam hingga menimbulkan suara kreeeek... kreeeek... yang menambah kesan menyeramkan.
Suara jangkrik terdengar bersahutan, sesekali diiringi lolongan anjing dari kejauhan. Angin berhembus lembab, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering.
Pak Asep menyorotkan senter ke depan, cahayanya menembus kabut tipis yang mulai turun di sela-sela batang bambu.
“Tempat ini dari dulu memang bikin merinding,” gumamnya pelan.
Ki Waryo berjalan paling depan dengan langkah tenang, tangannya menggenggam tongkat kayu tua
“Bambu ini bukan bambu biasa,” ujarnya lirih tanpa menoleh.
“Konon, dulu di sini tempat para leluhur menanam penanda wilayah. Tapi sekarang... sudah banyak yang tak suci lagi.”
Samidin yang berjalan di belakang tiba-tiba menoleh ke kiri, merasa ada sesuatu bergerak di antara bambu.
“Pak… Pak, kayak ada yang ngikutin kita,” bisiknya ketakutan.
Joko langsung memegang lengan Samidin,
“Sudah, jangan bicara aneh-aneh dulu, Din. Kita bersama-sama saja.”
Namun Ki Waryo hanya berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu menggumamkan sesuatu dengan bahasa kuno yang bahkan Pak Arman dan Pak Asep tidak mengerti.
Setelah beberapa detik, angin yang tadi bertiup keras mendadak berhenti. Suara jangkrik pun ikut senyap.
Sunyi. Benar-benar sunyi.
Pak Arman menelan ludah, lalu bertanya pelan,
“Ada apa, Ki?”
Ki Waryo membuka matanya perlahan.
“Mereka sudah tahu kita datang,” katanya tenang tapi tegas.
“Mulai sekarang, jangan bicara sembarangan. Apa pun yang kalian dengar… jangan ditanggapi.”
Mereka semua saling pandang dengan wajah tegang, lalu melanjutkan langkah ke dalam kegelapan bambu yang makin pekat.
Ki Waryo menatap satu per satu wajah mereka dengan mata yang sabar namun tajam. Suaranya pelan, serak—tetap membuat semua tunduk memperhatikan.
“Nanti—kalau aku bilang, senter matikan. Langsung matikan. Jangan ada cahaya, jangan bersuara. Diam dan ikuti apa yang saya katakan”
Pak Arman, Pak Asep, Samidin, dan Joko saling berpandangan singkat lalu mengangguk. Ketegangan menjalari udara, tapi keseriusan Ki Waryo membuat semuanya tak berani menolak. Ki Waryo lalu mengambil selembar kain putih dari dalam jubahnya, mengibaskan sedikit, seolah mengusir sesuatu yang tak terlihat.
Mereka melangkah lagi. Jalan setapak makin menyempit, akar dan batu saling bersautan, dan kabut menebal seperti tirai tipis.
Di depan, terlihat sebuah batu besar berlumut—permukaan terukir simbol-simbol tua yang samar, seperti gerbang yang dibentuk alam dan waktu. Di sinilah Ki Waryo berhenti.
Ia menempatkan seikat bunga kantil di pangkal batu, membuka kendi tanah liat dan menaburkan beberapa tetes air ke permukaan ukiran. Suaranya bergumam dalam bahasa yang tak semua paham—doa atau mantera, nada-nadanya bergema pendek di antara batang bambu.
“Ini adalah batasnya,” kata Ki Waryo lirih.
“Di balik batu itu, aturan lain berlaku. Jangan nyalakan cahaya kecuali aku perintahkan. Mata mereka bisa melihat dari arah cahaya, tapi hati mereka takut pada kesunyian manusia yang tetap.”
Detik-detik terasa panjang. Ki Waryo menoleh, menatap setiap orang; pandangannya lama sekali pada Samidin dan Joko yang tampak pucat. Lalu, perlahan—dengan gerakan yang tenang tapi menentukan—ia mengangkat tongkatnya dan memukul lembut sisi batu. Suara ketukan kecil bergema. Dari kejauhan terdengar, untuk sesaat, gamelan yang samar—seperti menyambut atau menimbang.
“Ayo matikan… senter matikan,” ucap Ki Waryo akhirnya, suaranya datar.
Serentak mereka mematikan sumber cahaya: senter, obor kecur, api kecil yang masih menyala di ujung tongkat—semua padam. Sekejap, kegelapan menyelimuti. Namun kegelapan itu bukan ketiadaan: matanya masing-masing perlahan menyesuaikan, dan di dalam kegelapan muncul kedalaman lain—suara menjadi jelas, napas angin, desah kabut, langkah kecil seperti pasir digesek.
Sementara itu, di bukit Arga Dipa malam terasa begitu sunyi. Angin hanya sesekali berembus lembut, menggoyangkan dinding tenda yang kini tampak tenang setelah badai semalam.
Semua peserta KKN sudah tertidur pulas — Nando, Raka, Novi, Citra, dan Lala terlelap dalam kelelahan setelah perjalanan panjang. Hanya Leo yang masih terjaga, berbaring menatap langit-langit tenda dengan mata terbuka lebar.
Bayangan ular besar berwarna hitam legam yang dibunuh Nando beberapa jam lalu terus terbayang di pikirannya. Ia bisa melihat lagi bagaimana tubuh ular itu meliuk perlahan sebelum akhirnya diam tak bergerak, dan bagaimana tatapan mata Nando saat memukulinya — tajam, tapi… aneh.
“Aneh, padahal Nando biasanya takut ular kecil aja udah kabur,” gumam Leo pelan, hampir tak bersuara.
Ia berguling ke sisi kanan, mencoba memejamkan mata, tapi bunyi
“krek… krek…” dari luar tenda membuatnya terjaga lagi. Leo menahan napas, berusaha mendengarkan lebih jelas. Awalnya ia mengira itu cuma suara ranting jatuh tertiup angin, tapi suara itu terus berulang, seperti langkah pelan yang mengitari tenda.
“Mungkin cuma hewan…” pikirnya menenangkan diri, meski bulu kuduk mulai berdiri.
Leo yang refleks menoleh ke arah Raka, berharap sahabatnya itu terbangun, justru terlonjak kaget.
Di balik cahaya redup dari sisa api unggun yang menembus kain tenda, ia melihat Nando kini berada di atas tubuh Lala, kedua tangannya menekan kuat leher gadis itu.
Lala meronta, kakinya menendang-nendang tak beraturan. Suara napasnya terdengar tersengal, mencoba berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan.
“Allahuakbar!! Nando, lepasin!!” teriak Leo dengan panik.
Leo berlari dan menarik tangan Nando dengan sekuat tenaga, tapi cengkeraman itu justru semakin kuat — jari-jari Nando menancap di kulit leher Lala, membuat gadis itu terbatuk dan menangis kesakitan.
“Nando! Lepasin dia!!” teriak Leo panik.
Namun belum sempat ia menarik lebih jauh, Nando membalikkan wajahnya perlahan ke arah Leo.
Cahaya senter yang bergetar di tangan Leo menyorot wajah Nando… dan saat itu juga Leo menjerit ketakutan.
Wajah sahabatnya kini penuh darah, matanya terbelalak tanpa bola mata, hanya rongga hitam pekat meneteskan cairan merah. Dari mulutnya menetes darah segar bercampur tanah, sementara lidahnya menjulur seperti ular.
“Allahuakbar…!” teriak Leo sambil mundur terhuyung.
Nando menatapnya tajam — atau entah apa yang kini mengendalikan tubuh itu — lalu mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya sendiri.
Suara itu serak, seperti berasal dari perut bumi.
“Sudah… giliran kalian…”
Tiba-tiba Leo merasa ada yang menetes di wajahnya—dingin dan membasahi pipinya. Ia tersentak bangun dengan napas terengah, matanya langsung terbuka lebar. Ternyata bukan darah, bukan Lala yang dicekik, melainkan tetesan air dari tangan Raka yang mengguyurkan sedikit air ke wajahnya.
“Leo! Bangun, woi!” ujar Raka dengan wajah khawatir.
Leo masih gemetar, matanya berkedip cepat sambil terus mengucap istighfar,
“Astaghfirullah... astaghfirullah aladzim...” suaranya bergetar, cukup keras hingga membuat Dimas dan Bima yang sedang berbaring ikut menoleh.
“Woi, kenapa lo?” tanya Raka, yang masih memegang botol air mineral di tangannya.
Leo menatap mereka satu per satu, wajahnya pucat.
“Aku... aku mimpi Nando... dia—dia...” suaranya tercekat, tenggorokannya terasa kering.
Leo menatap mereka satu per satu, wajahnya pucat.
“Aku... aku mimpi Nando... dia—dia...” suaranya tercekat, tenggorokannya terasa kering.
Raka memegang bahunya, mencoba menenangkan.
“Udah, tenang dulu. Mimpi aja itu, Le. Tadi lo manggil-manggil nama Nando sambil istighfar keras banget.”
Leo menarik napas panjang, masih belum percaya apa yang baru dialaminya.
“Tapi rasanya nyata banget, Rak... dia kayak... beneran di depan aku.”
“Lu pasti gak baca doa kan tadi sebelum tidur makannya sampai mimpi buruk,” ucap Raka sambil memberikan sehelai baju untuk membersihkan sisa air dari wajah Leo.