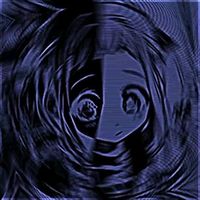Enam mahasiswa—Raka, Nando, Dimas, Citra, Lala, dan Novi—memutuskan untuk menghabiskan libur semester dengan mendaki sebuah bukit yang jarang dikunjungi di pinggiran kota kecil. Mereka mencari petualangan, udara segar, dan momen kebersamaan sebelum kembali ke rutinitas kampus. Namun, yang mereka temukan bukanlah keindahan alam, melainkan kengerian yang tak terbayangkan.
Bukit itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Menurut penduduk setempat, kawasan itu dijaga oleh makhluk halus yang disebut “penunggu hutan”, sosok jin yang berwujud manusia tampan dan wanita cantik, yang gemar memperdaya manusia muda untuk dijadikan teman di alam mereka. Awalnya, keenamnya menertawakan cerita itu—hingga malam pertama di hutan tiba.
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Juan Darmawan, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
Rencana Pendakian Malam Jum'at Kliwon
Pak Asep menatap ke arah jalan setapak yang mengarah ke ujung desa, suaranya berat tapi mantap.
“Kalau begitu saya siap-siap dulu, Man. Ki Waryo kalau ndak ada di rumahnya, sudah pasti di ladangnya… dan ladangnya itu jauh, di ujung kebun kopi dekat batas hutan.”
Pak Arman mengangguk cepat.
“Baik, saya tunggu di sini aja ya, Sep?”
Pak Asep bergegas masuk ke rumah, mengambil jaket tebal, celana lapangan, dan sebuah golok pendek yang biasa ia bawa kalau masuk hutan. Dari dapur, istrinya sempat bertanya cemas,
“Pak, mau kemana jangan bilang bapak mau naik ke gunung Arga Dipa,"
“Saya harus menemui Ki Waryo kuncen gunung Arga Dipa Bu cuma beliau yang bisa membantu kita ”
Bu Mina menatap suaminya dengan wajah cemas, tangannya refleks meraih lengan Pak Asep sebelum lelaki itu benar-benar melangkah pergi.
“Ya sudah, bapak hati-hati ya…” katanya lirih, matanya tampak bergetar menahan kekhawatiran.
Pak Asep tersenyum tipis, mencoba menenangkan istrinya meski hatinya sendiri tidak tenang.
“Iya, Bu. Doain aja, semoga Ki Waryo masih di rumahnya kalau begitu kan saya sama Pak Arman Ndak harus ke ladangnya, Kalau beliau ada, insyaallah semua bisa dijelaskan"
Bu Mina mengangguk pelan.
“Kalau ketemu, titip salam saya ya, Pak. Bilang… jangan biarkan anak-anak itu kenapa-kenapa.”
Pak Asep hanya mengangguk. Ia tahu betul istrinya juga ikut gelisah sejak tadi pagi, terlebih setelah kabar dari Pak Arman tentang para mahasiswa yang nekat mendaki.
Ia kemudian menurunkan pandangannya, memastikan golok terselip aman di pinggang dan jaketnya terpasang rapat.
“Saya berangkat dulu, Bu. Jangan lupa tutup pintu, dan kalau ada angin aneh dari arah gunung, jangan keluar rumah, ya.”
Bu Mina terdiam sejenak, lalu menjawab pelan,
“Iya, Pak… saya tunggu.”
Pak Arman berdiri di depan rumah Pak Asep sambil mengecek rantai sepedanya yang sudah tua, terdengar bunyi krek-krek kecil setiap kali ia putar pedalnya. Tak lama kemudian, Pak Asep keluar dari rumah dengan wajah serius, jaket tebal sudah terpasang, dan golok terselip di pinggang.
“Sudah siap, Sep?” tanya Pak Arman.
“Siap, Man. Kita langsung ke rumahnya Ki Waryo aja, siapa tahu beliau belum ke ladang,” jawab Pak Asep sambil menaiki sepeda batangnya yang catnya sudah pudar.
Mereka berdua mulai mengayuh perlahan di jalan desa yang tampak sepi hanya ada beberapa rumah yang tampak ada penghuninya. Roda sepeda menimbulkan bunyi krek-krek di atas jalan tanah yang sedikit berbatu-batu.
“Sep,” ujar Pak Arman pelan sambil mengayuh,
“kalau sampai anak-anak itu ndak bisa ditemukan, bagimana?”
Pak Asep menatap lurus ke depan, matanya tajam tapi muram.
“Jangan berprasangka burik begitu dulu, Man. Selama Ki Waryo masih ada, kita masih bisa minta petunjuk.”
...****************...
Beberapa menit kemudian, setelah melewati jalan berbatu yang sedikit menanjak, akhirnya Pak Arman dan Pak Asep tiba di depan rumah panggung tua milik Ki Waryo.
Rumah itu berdiri di tengah kebun bambu, sebagian dindingnya sudah lapuk dimakan usia, namun di berandanya masih tampak rapi.
Pak Arman menghentikan sepedanya, menatap ke arah pintu yang sedikit terbuka.
“Sep, sepertinya beliau ada di rumah. Lihat itu, masih ada asap di dapur.”
Belum sempat mereka mengetuk, terdengar suara serak namun tegas dari dalam rumah:
“Masuk saja, Asep… Arman… saya sudah tahu kalian datang.”
Mereka saling berpandangan sejenak. Pak Asep menelan ludah, lalu melangkah perlahan menaiki tangga kayu. Di dalam rumah, Ki Waryo duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan baju putih longgar dan kain hitam di kepalanya. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan dalam.
“Assalamu’alaikum, Ki,” ucap Pak Asep dengan hormat.
“Wa’alaikum salam,” jawab Ki Waryo tanpa membuka mata. “Kalian datang karena anak-anak itu, kan?”
Pak Arman langsung mengangguk.
“Iya, Ki… mereka tujuh orang mahasiswa. Sejak pagi kami dapat kabar mereka sudah naik ke Arga Dipa. Kami khawatir, Ki, apalagi sekarang bulan Juni.”
Ki Waryo membuka matanya perlahan, tatapannya tajam menembus keduanya.
“Kalian tahu apa artinya bulan Juni di Arga Dipa?” tanyanya pelan.
Pak Asep menjawab dengan nada berat,
“Bulan di mana Dewi Pertiwi meminta tumbal…”
Ki Waryo mengangguk lambat, lalu menghela napas panjang.
“Benar. Dan kali ini… aku sudah mencium tandanya sejak tiga malam lalu. Angin dari arah puncak membawa bau anyir tanah basah. Itu tandanya gerbang lama mulai terbuka.”
Pak Arman menatap Ki Waryo dengan tegang.
“Gerbang lama? Maksudnya jalur yang sudah ditutup itu, Ki?”
Ki Waryo mengangguk lagi, pandangannya kosong ke arah luar jendela.
“Mereka mungkin sudah melewati batas itu tanpa sadar…”
Suara angin berhembus di sela bambu, membuat suasana di dalam rumah makin mencekam.
“Kalau begitu, Ki,” ujar Pak Asep pelan, “apa yang harus kita lakukan?”
Ki Waryo menutup matanya lagi, lalu berkata dengan lirih namun tegas,
“Kita harus menyusul mereka. Dan kita harus berangkat di hari Jumat nanti tepat di malam Jum'at kliwon”