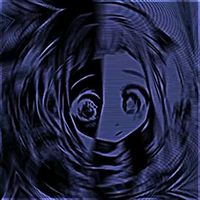Enam mahasiswa—Raka, Nando, Dimas, Citra, Lala, dan Novi—memutuskan untuk menghabiskan libur semester dengan mendaki sebuah bukit yang jarang dikunjungi di pinggiran kota kecil. Mereka mencari petualangan, udara segar, dan momen kebersamaan sebelum kembali ke rutinitas kampus. Namun, yang mereka temukan bukanlah keindahan alam, melainkan kengerian yang tak terbayangkan.
Bukit itu ternyata menyimpan rahasia kelam. Menurut penduduk setempat, kawasan itu dijaga oleh makhluk halus yang disebut “penunggu hutan”, sosok jin yang berwujud manusia tampan dan wanita cantik, yang gemar memperdaya manusia muda untuk dijadikan teman di alam mereka. Awalnya, keenamnya menertawakan cerita itu—hingga malam pertama di hutan tiba.
Karya ini diterbitkan atas izin NovelToon Juan Darmawan, isi konten hanyalah pandangan pribadi pembuatnya, tidak mewakili NovelToon sendiri
Menuju Puncak Bukit Arga Dipa
Pak Arman mengangguk pelan sambil menatap langit yang mulai cerah, meski entah kenapa dadanya terasa berat.
“Baiklah, Sep… nanti sore kita ke rumah Ki Waryo. Kita tanya dulu, apa benar malam ini waktu yang tepat buat naik.”
Pak Asep merapikan pecinya, lalu menaiki sepedanya.
“Iya, Man. Saya pamit dulu, mau siapin bekal sama peralatan. Nanti menjelang magrib saya ke sini lagi.”
“Baik, Sep. Hati-hati di jalan,” jawab Pak Arman.
Bu Siti keluar dari dapur sambil mengelap tangannya dengan kain kecil. Dari tadi ia memperhatikan suaminya yang hanya duduk diam di kursi bambu dekat jendela, menatap ke arah gunung tanpa berkata apa-apa.
“Bapak kenapa?” tanya Bu Siti pelan sambil duduk di sampingnya.
Pak Arman menarik napas panjang sebelum menjawab.
“Saya cuma kepikiran, Bu… anak-anak mahasiswa itu. Dari kemarin belum ada kabar. Cuaca juga nggak menentu.”
Bu Siti ikut menatap ke luar jendela, ke arah puncak Arga Dipa yang masih diselimuti kabut tipis meski matahari sudah mulai tinggi.
“Semoga mereka baik-baik saja, Pak.”
Pak Arman menggeleng pelan.
“Ndak tahu kenapa, hati saya nggak enak, Bu. Apalagi tadi malam hujan deras, petir menyambar terus ke arah gunung.”
"Sepertinya ada yang Ndak beres dengan anak kita Bu"
“Anak kita? Maksud Bapak siapa? Kan Aisyah di rumah, Ndak ke mana-mana…”
"Tadi waktu Aisyah pulang dari sungai saya lihat ada genderuwo mengikuti dia,"
”
Bu Siti langsung membelalak kaget, wajahnya memucat. Ia refleks menoleh ke arah dalam rumah, memastikan Aisyah benar-benar sudah di dalam kamar.
“Astaghfirullah, Pak… jangan ngomong sembarangan begitu! Mungkin Bapak salah lihat, capek kali, ya?” katanya berusaha menenangkan diri, meski suaranya bergetar.
Pak Arman menggeleng pelan.
“Saya tahu apa yang saya lihat, Bu. Badannya besar… hitam legam, matanya merah nyala. Dia berdiri di belakang Aisyah waktu anak itu manggil saya tadi.”
Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan, menahan rasa takut.
“Terus… apa maksudnya, Pak? Kenapa bisa ikut pulang sama Aisyah?”
Pak Arman memandang ke arah pintu kamar Aisyah, napasnya berat.
“Saya ndak tahu, Bu. Tapi biasanya, kalau makhluk itu sampai berani ikut dari sungai… berarti ada sesuatu yang dia cari.”
“Jangan bilang, Pak, itu ada hubungannya sama anak-anak mahasiswa yang naik ke gunung Arga Dipa itu…”
Pak Arman terdiam, hanya menatap kosong ke lantai tanah rumah mereka. Angin sore masuk dari celah jendela,
“Kita berdoa saja Bu semoga Ndak ada sesuatu yang akan terjadi dengan anak kita,”
Tanpa Pak Arman dan Bu Siti sadari di semak-semak samping rumahnya ada seorang pria yang tersenyum sinis sambil memperhatikan pasangan suami istri itu.
“Lihat saja Arman sebentar lagi kamu akan menangis darah melihat putri semata wayangmu,"
...****************...
Di puncak bukit Arga Dipa para mahasiswa itu mulai menapaki jalur setapak lagi. Tanahnya lembap setelah hujan semalam, dedaunan meneteskan air yang jatuh perlahan ke pundak mereka. Suasana hutan terasa tenang, cahaya matahari mulai menembus celah-celah dedaunan dan pepohonan.
Suara burung juga terdengar berkicau menciptakan suasana tenang suasana yang tidak pernah di rasakan di kota selama ini.
Raka berjalan paling depan sambil sesekali melihat peta.
“Kalau sesuai peta, kita udah gak jauh lagi dari pos keempat. Abis itu tinggal setengah jam jalan ke puncak.”
Novi menatap ke arah langit yang mulai cerah.
“Syukurlah hujan udah berhenti. Tapi kenapa ya, jalanan kayak makin sempit gini?”
Citra menimpali sambil memegangi pergelangan tangannya yang tergores ranting,
“Mungkin karena udah jarang dilewatin. Tuh, liat aja, semak udah nutup semua jalur.”
Sementara itu, Lala yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Ia menatap ke sisi kanan jalur, di mana ada sesuatu seperti potongan kain merah yang tersangkut di ranting pohon.
“Eh… ini kain apa ya? Kayak kain bekas gitu,” katanya pelan.
Nando yang berada tak jauh di belakang menatap kain itu lama. Wajahnya tampak kaku — warna merah lusuh itu mirip dengan kain dari sosok wanita yang ia lihat semalam menari di tengah hujan.
“Buang aja, La. Jangan dipegang,” ucap Nando cepat, nadanya agak tinggi.
Lala menatap Nando heran, tapi menurut saja. Ia menjauh dari ranting itu.
Leo yang berjalan di belakang Nando melihat Nando tampak lemas Leo bertanya
"Lu kenapa Ndo kok lemas gitu?' Nando menjawab
"Gue capek"
Leo memperhatikan wajah Nando yang tampak pucat dan berkeringat, meski udara di sekitar mereka dingin. Nafasnya terlihat berat, langkahnya juga mulai goyah.
“Capek gimana? Kita baru jalan setengah jam, Ndo,” kata Leo khawatir sambil mendekat.
"Gue bukan capek gimana gue cuma capek lihat bokap sama nyokap gue tiap hari ribut udah gitu kalau ribut gak ada obatnya”
Leo terdiam mendengar jawaban itu. Ia sempat mengira Nando hanya kelelahan fisik, tapi ternyata lain. Nada suara Nando terdengar berat, penuh tekanan yang selama ini dipendam.
“Gue tuh cuma pengen tenang, Yo… makanya gue ajak kalian naik gunung ini. Pengen jauh dari rumah, jauh dari ribut-ribut gak jelas.”
Lala yang berjalan di depan ikut menoleh, wajahnya ikut melunak.
“Kasihan juga ya, Ndo gue gue juga sebenarnya ngalamin hal yang sama…” gumamnya pelan.
Nando menarik napas panjang, matanya menatap ke langit.
“Kadang gue mikir, apa salah gue sampai harus dengerin mereka saling maki tiap hari. Gue capek, Yo… capek banget.”
Leo menepuk bahu Nando dan Lala pelan.
“Kalian yang sabar, Ndo La. Kadang orang tua juga punya masalah sendiri yang kita gak ngerti. Tapi lu gak sendirian, bro, kita di sini bareng.”
Nando tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada sorot mata kosong — seperti menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar lelah batin.
“Iya, makasih, Yo… tapi kadang gue ngerasa kayak… semuanya udah gak ada gunanya.”
"Pulang dari sini kalau orang tua kalian ribut kalian datang aja ke rumah gue di jamin aman"
Nando dan Lala menoleh ke arah Leo, matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tersenyum kecil, kali ini lebih tulus.
“Serius, Le? Lu gak bakal keberatan?”
Leo mengangguk mantap.
”Ya iyalah. Nyokap gue orangnya juga enak, santai. Kadang rumah rame tuh justru bikin adem. Kalian datang aja, nginep juga gak apa-apa. Di rumah gue gak bakal ada yang ribut.”
Mendengar ucapan Leo, suasana jadi hangat kembali. Novi tersenyum sambil menepuk bahu Leo,
“Wah, kalau gitu nanti kita mampir beneran ya, Yo. Janji nih jangan cuma omongan doang.”
Raka menimpali dengan nada bercanda,
“Asal jangan disuruh bantu cuci piring aja, gue langsung kabur.”
Semua tertawa, bahkan Nando dan Lala pun ikut tersenyum tipis.